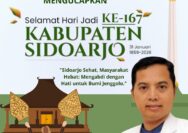Bangjo.co.id | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sejatinya lahir sebagai tonggak reformasi, menjamin kemerdekaan pers dan membebaskan media dari kontrol kekuasaan. Namun, seperempat abad berlalu, realitas industri media telah berubah drastis, dan UU Pers tampak semakin tertinggal dalam menjawab tantangan zaman.
Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, disrupsi digital, serta tekanan finansial dan politik, pekerja media Indonesia kini terjerumus dalam status “precariat” kelas pekerja tanpa jaminan, tanpa perlindungan, dan tanpa masa depan yang pasti. Ironisnya, UU Pers tidak memberi jaminan sosial, upah layak, atau perlindungan kerja bagi jurnalis yang semakin banyak bekerja tanpa kontrak tetap. Ini menjadi paradoks: jurnalis dijamin kebebasan menulis, tetapi tidak dijamin hidupnya.
UU Pers terlalu fokus pada idealisme kebebasan, tetapi minim mekanisme perlindungan struktural dalam industri yang telah berubah menjadi arus bisnis korporat dan algoritma. Tidak ada regulasi yang melindungi jurnalis freelance, tidak ada sanksi bagi perusahaan media yang menggaji di bawah upah minimum, dan tidak ada intervensi negara yang nyata ketika gelombang PHK massal terjadi di berbagai ruang redaksi.
Situasi ini makin genting ketika iklim media Indonesia kini dikendalikan oleh kepentingan iklan politik, belanja BUMN, serta dominasi platform digital global seperti Meta dan Google yang menyerap 75% belanja iklan nasional. UU Pers gagal menjawab tantangan struktur ekonomi baru ini, dan tidak memberikan mekanisme fiskal yang bisa menopang keberlangsungan media independen.
Yang lebih mengkhawatirkan, regulasi baru seperti PP Nomor 28 Tahun 2024, yang membatasi iklan tembakau tanpa kompensasi bagi media, justru makin mempersempit ruang napas media lokal, tanpa dibarengi skema subsidi atau “media pluralism fund” yang lazim di negara demokratis. Hasilnya, media dipaksa untuk tunduk pada kekuatan pasar, dan jurnalis dipaksa untuk mengorbankan etika demi bertahan hidup.
Dalam konteks ini, UU Pers harus direvisi secara menyeluruh, bukan hanya untuk menjaga kemerdekaan redaksi, tetapi untuk menjamin kesejahteraan pekerja media, menyesuaikan ekosistem digital, dan menata ulang ekonomi politik media agar tetap relevan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
UU Pers yang tidak menjamin pendapatan layak, tidak mengatur relasi kerja secara adil, dan tidak melindungi independensi media dari intervensi pemilik modal dan kekuasaan politik telah menjadi regulasi kosong di tengah krisis jurnalisme.
Jika negara terus membiarkan jurnalis berada dalam kondisi “hidup segan, mati tak mampu,” maka bukan hanya kualitas jurnalisme yang runtuh, tetapi fungsi media sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi juga ikut lenyap.
Kritik terhadap UU Pers bukan berarti menolak kemerdekaan pers justru sebaliknya, demi menyelamatkan esensi kemerdekaan itu sendiri. Karena tanpa perlindungan ekonomi, tak ada kebebasan yang bisa dipertahankan.