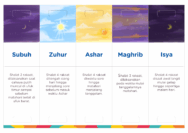Bangjo.co.id – Mereka tertawa dalam sebuah rekaman pendek yang beredar cepat — tawa yang, beberapa jam kemudian, berubah menjadi gema amarah publik. Di kursi pengemudi sebuah mobil, seorang pria berbicara ringan tentang perjalanan menuju Makassar.
Di sampingnya duduk seorang wanita. Kata-kata yang keluar dari mulut sang pria bukan candaan kosong: “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin.”
Klip itu, yang merebak ke berbagai kanal media sosial dan berita, memantik pertanyaan paling sederhana dan paling menyakitkan: bagaimana bisa seorang wakil rakyat melontarkan gagasan merampok negara sambil tertawa? Ada lapisan malu yang pekat dalam adegan itu.
Suara yang seharusnya merepresentasikan kepercayaan publik berubah menjadi pengakuan yang mempermalukan. Tak lama setelah video tersebar, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memanggil sang politisi untuk memberikan klarifikasi. Dalam pemeriksaan itu terungkap klaim yang kelak menjadi bagian narasi resmi: Wahyudin Moridu menyatakan bahwa ia sedang dalam kondisi mabuk dan tidak menyadari bahwa ucapannya terekam. Penyelidikan internal pun dimulai.
Sehari setelah gegap gempita viral, konsekuensi politik datang cepat. DPP PDI Perjuangan mengeluarkan keputusan tegas: memecat anggota DPRD tersebut. Partai menilai ucapan itu melukai citra wakil rakyat dan tak dapat ditoleransi. Segera pula wacana pergantian antar waktu (PAW) mengemuka—sebuah pengingat bahwa nama besar institusi bisa runtuh oleh satu video singkat.
Di ranah publik juga muncul sisi lain cerita: ada laporan yang menyebut video itu direkam oleh seorang wanita yang disebut sebagai “pacar gelap” sang politisi — motifnya, menurut beberapa liputan, karena permintaan untuk dinikahi tidak dipenuhi. Jika benar, lapisan pribadi ini menambah rasa pilu: bukan hanya wakil rakyat yang tersandung, tetapi kehidupan privat yang tumpah ke ruang publik, memperburuk luka reputasi dan moral.
Ada bodek lain yang membuat cerita ini terasa lebih sinis: pemeriksaan dokumen harta pribadi. Laporan LHKPN menunjukkan kekayaan yang kurang mengesankan — kas kecil, utang, hingga total yang hampir nol atau minus — sehingga pernyataan tentang “merampok uang negara” berubah menjadi ironi pahit ketika diletakkan di samping realitas ekonomi sang politisi. Nada sarkastik publik bukan tanpa alasan: janji menjaga kepentingan rakyat, dalam sekejap, dibenturkan dengan sikap acuh adu domba yang tampak di layar.
Lebih dari sanksi politik, kejadian ini membuka luka kolektif: kepercayaan yang terkikis, harapan representasi yang ternodai. Ada yang marah, ada yang menertawakan, ada pula yang sekadar bersedih — bukan hanya untuk satu jasmani yang jatuh derajatnya, tetapi untuk gagasan bahwa wakil rakyat adalah penjaga amanah. Ketika kata-kata menjadi bukti, tanggung jawab tak lagi sekadar retorika; ia mengikat dengan konsekuensi nyata.
Namun cerita ini juga memperlihatkan satu hal lain yang patut direnungkan: kecepatan informasi. Video singkat, direkam di sudut pribadi, dalam hitungan jam memicu pemeriksaan resmi, keputusan partai, dan ruang opini publik. Era di mana sebuah momen kebodohan atau kecerobohan dapat melumat reputasi dalam hitungan detik juga mengharuskan kita menimbang: adakah mekanisme pemulihan yang manusiawi ketika seseorang—apapun jabatan atau kesalahannya—hendak mengambil tanggung jawab kembali?
Wahyudin, dalam permohonan maaf yang direkam kemudian, tampak menanggung beban. Ia meminta maaf kepada publik dan menyatakan siap menerima konsekuensi. Namun maaf, dalam lanskap publik yang mudah terpolarisasi, tidak selalu menuntut proses pemulihan yang sederhana. Ada reputasi yang harus diperbaiki, ada lembaga yang harus pulih dari pukulan kepercayaan, dan ada warga yang menuntut keteladanan.
Di ujung cerita, kita kembali pada dua hal yang tak elok dipisahkan: kata dan perbuatan. Seorang wakil rakyat bukan hanya wajah di baliho; ia juga bibir dan tindakan. Ketika bibir itu mengucap sesuatu yang merendahkan nilai publik — bahkan dalam keadaan mabuk atau dalam keliru privasi — efeknya meluas: mengguncang kepercayaan, memicu proses hukum-partai, dan mengundang tanya besar tentang kualitas moral pejabat publik.
Yang mungkin paling pilu adalah bagaimana sebuah tawa di dalam mobil bisa berubah menjadi denting yang membangunkan kita semua. Denting itu menegur: kewenangan tanpa integritas akan runtuh — dan ketika ia runtuh, yang paling merana bukan satu orang saja, melainkan rasa aman publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga mereka.
( Hamzah )