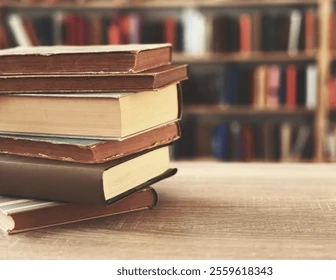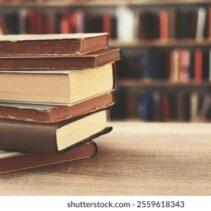Bangjo. co. id – Penangkapan Ahmad Faiz di Kediri dan penyitaan sejumlah buku darinya, termasuk karya Bob Black The Abolition of Work, memperlihatkan wajah lama negara: takut pada gagasan. Sebuah buku dianggap berbahaya, seolah-olah membaca adalah kejahatan. Padahal, sepanjang sejarah, yang paling sering membakar, melarang, dan menyita buku bukanlah mereka yang percaya diri dengan kekuasaan, melainkan justru mereka yang rapuh, yang gelisah menghadapi kemungkinan warganya berpikir berbeda.
Siapakah Bob Black? Ia seorang penulis anarkis asal Amerika Serikat yang terkenal lewat esainya The Abolition of Work (1985). Kalimat pembukanya sudah cukup untuk mengguncang moralitas kerja: “No one should ever work.” Tidak seorang pun seharusnya bekerja.
Black mendefinisikan kerja sebagai forced labor—produksi yang dipaksakan, baik oleh kebutuhan ekonomi maupun tekanan politik. Dengan kata lain, kerja dalam masyarakat modern tidak lebih dari perbudakan yang disamarkan. Buruh memang menerima gaji, tetapi pada saat yang sama ia kehilangan tubuh, waktu, dan bahkan imajinasinya yang terus dikontrol oleh majikan maupun negara.
Solusi yang ditawarkan Black bukanlah kemalasan pasif, bukan pula berhenti beraktivitas. Ia mengusulkan transformasi radikal: mengganti kerja paksa dengan permainan (play). Dalam dunia permainan, orang beraktivitas karena kehendak, rasa ingin tahu, atau kegembiraan—bukan keterpaksaan. Hidup manusia bisa dijalani secara lebih bebas, kreatif, dan bermakna.
Gagasan ini jelas utopis. Dalam masyarakat kapitalis, hampir mustahil manusia benar-benar lepas dari kerja upahan. Tetapi utopisitas inilah yang penting: ia membuka horizon bahwa dunia yang kita jalani hari ini bukan satu-satunya kemungkinan. Rasa lelah, keterasingan, dan keterpenjaraan di tempat kerja bukanlah takdir, melainkan hasil konstruksi sosial yang bisa—dan seharusnya—digugat.
Membaca Bob Black di Indonesia, wajar bila sebagian orang mengernyit. Kita hidup dalam budaya yang memuja kerja keras sebagai moralitas. Seseorang yang rajin dianggap terhormat, sementara pengangguran dicap gagal, malas, bahkan kriminal. Dari sekolah, mimbar agama, hingga pidato pejabat, kita disuguhi pesan yang sama: kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan, kesejahteraan, dan kemuliaan.
Di titik inilah negara menjadi gelisah. Bila gagasan Bob Black beredar luas, orang bisa mulai mempertanyakan dogma lama: mengapa kita harus terus bekerja bahkan hingga melupakan hidup itu sendiri? Mengapa pengangguran selalu diperlakukan sebagai masalah, padahal ia juga bisa dipahami sebagai perlawanan terhadap sistem kerja yang eksploitatif?
Negara modern berdiri di atas logika produktivitas. Ia memerlukan warga yang taat, patuh, dan giat bekerja, sebab dari situlah pajak, stabilitas, dan legitimasi diperoleh. Maka wajar bila gagasan yang menolak kerja dipandang subversif. Dalam kacamata aparat, buku Bob Black bukan lagi teks pemikiran, melainkan ancaman terhadap fondasi politik dan ekonomi negara.
Namun kasus Ahmad Faiz tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah kelanjutan dari tradisi panjang represi literatur di Indonesia. Kita ingat bagaimana karya-karya Pramoedya Ananta Toer dibakar dan dilarang pada masa Orde Baru. Kita ingat suara Wiji Thukul, penyair yang berani menggugat penguasa, dibungkam hingga ia sendiri hilang tanpa jejak. Kita pun tahu bagaimana buku-buku Karl Marx, Lenin, atau sekadar terjemahan filsafat politik Eropa dilarang beredar dengan dalih membahayakan negara.
Pasca-reformasi 1998, kita sempat berharap represi itu berakhir. Terlebih sejak 2010, pemerintah tidak lagi memiliki dasar hukum formal untuk melarang buku, karena Keppres yang memberi kewenangan tersebut sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Tetapi praktiknya, pelarangan dan penyitaan tetap berulang—tanpa landasan hukum yang sah. Buku-buku tentang 1965, literatur anarkis, atau diskusi teks kiri kontemporer kerap dibubarkan aparat dengan alasan keamanan.
Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa negara tidak pernah benar-benar percaya pada rakyatnya untuk berpikir. Negara selalu takut bila warganya membaca, merenung, lalu menemukan cara berpikir di luar nalar resmi yang ditawarkan.
Kasus Ahmad Faiz juga menyingkap peran negara bukan hanya sebagai pengendali tenaga kerja, tetapi juga sebagai “majikan wacana”. Seperti halnya majikan di pabrik yang mengatur jam, ritme, dan gerak buruh, negara juga mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibaca, didiskusikan, atau dipikirkan.
Penyitaan buku Bob Black memperlihatkan ironi itu: sebuah teks yang mengkritik kerja paksa justru menjadi bukti bahwa negara memang gemar memaksa, bahkan dalam ranah intelektual. Negara tidak hanya mengatur tubuh, tapi juga mengatur imajinasi.
Opini saya sederhana: buku tidak pernah bersalah. Sebuah teks hanyalah kata-kata di atas kertas. Yang berbahaya bukan bukunya, melainkan ketakutan negara terhadap kebebasan berpikir. Ketika aparat menyita buku, yang sebenarnya mereka sita adalah peluang orang untuk bertanya, berdiskusi, dan meragukan status quo.
Penyitaan buku Ahmad Faiz bukanlah upaya menjaga ketertiban, melainkan cara negara melindungi diri dari kritik. Padahal justru perdebatan tentang kerja, negara, dan kebebasan itulah yang kita butuhkan untuk membangun masyarakat yang sehat.
Negara boleh menyita buku, tapi ia tak bisa menyita keresahan. Dari Pramoedya, Wiji Thukul, hingga Ahmad Faiz, sejarah menunjukkan bahwa gagasan selalu menemukan jalannya untuk hidup. Kertas bisa hangus, rak buku bisa kosong, diskusi bisa dibubarkan—tetapi pikiran tak pernah bisa dibredel.
Mungkin benar, membaca Bob Black tidak serta-merta mengubah dunia. Tetapi membungkam orang yang membaca Bob Black jelas memperlihatkan sesuatu yang lebih penting: ketakutan negara akan dunia yang bisa berubah. Dan selama ketakutan itu ada, buku-buku akan tetap lahir, gagasan akan tetap beredar, dan perlawanan akan selalu menemukan rumahnya. (*)